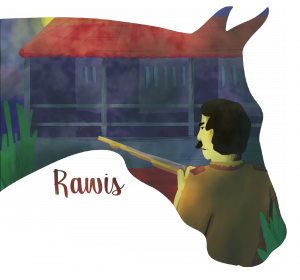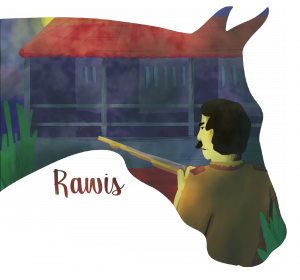oleh Ardi Wina Saputra
Riuh gemuruh kalbu dalam degub jantungku tak pernah berhenti menanak risau walau sejenak. Setiap tamu yang kujamu semalam suntuk selalu terenggut nyawanya ketika surya mulai membersitkan cahaya dari ufuk timur. Kepalaku berdesir membayangkan hal muram tak karuan. Sempat aku mengutuk langit melontarkan sumpah serapah agar tak turun lagi malaikat pencabut nyawa di atas atap rumahku. Namun semua sia-sia, langit hanya membisu dengan semilir angin memporakporandakan setiap helaian ujung rambutku. Aku pun menghentakkan kaki ke tanah sekeras mungkin, berharap agar dewa neraka terusik dan keluar menjelaskan sebab musabab diseretnya tamu-tamuku ke api pencucian. Sungguh hal itu juga sia-sia. Ah sudahlah, aku telah termakan takhayul rakyat jelata yang mengatakan bahwa rumahku dikutuk oleh jin dan sebangsa gaib lainnya. Semakin kudengar perkataan para budak pribumi itu, semakin tak waras aku dibuatnya.
Oh tamu-tamuku. Padahal mereka bukanlah orang sembarangan, mereka adalah para pembesar, pejabat, bangsawan, bahkan para tuan tanah Semarang. Tim penyidik utusan Gouverneur General dari Balai Kota telah berkali-kali memeriksa rumah ini, namun sayang hasilnya nihil. Tak ditemukan jejak, sidik jari, bahkan satu pun barang bukti yang membuktikan tindak pembunuhan. Mereka bahkan seringkali menutup kasusnya di tengah jalan, bahkan beberapa malah menyerah dan menyuruhku untuk melaporkan pada dukun setempat.
Sempat aku berpikir ada musuh dalam selimut yang berkedok sebagai pegawaiku. Parahnya aku sempat melakukan praduga tak bersalah terhadap setiap jongos, kurir, hingga penjaga rumah yang berkulit pribumi. Mereka kubariskan berjajar dan kupukul dengan cambuk berduri agar mau mengakui kesalahannya. Namun percuma, hingga mereka bersimbah darah pun tak ada yang mau mengaku. Sejak itu aku tak mempekerjakan mereka lagi dan memulangkannya dalam keadaan cacat. Harusnya mereka masih berterimakasih padaku karena tak kujadikan sebagai sarapan para buaya di kolam belakang rumah.
Kecurigaan konyolku itu ternyata tak terbukti, setelah aku mengganti seluruh pekerja dan penjaga di rumahku dengan orang-orang sebangsaku, kasus pembunuhan tetap saja meneror rumah ini. Bahkan satu per satu dari mereka lah yang mati saat tidak ada tamu menginap di rumah ini. Sungguh lawanku kurang ajar. Di luar rumah, aku sangat disegani bahkan serdadu KNIL pun tunduk atas perintahku tapi sayang di dalam rumah aku hanya dipermainkan oleh kematian-kematian beruntun orang di sekelilingku.
Dari berbagai kasus itu sebenarnya hanya satu yang kukhawatirkan, yaitu nyawa puteri semata wayangku, Helena. Aku sendiri sudah tak khawatir dengan kematianku sendiri. Tugasku tak lepas dari maut. Sebagai mayoor tertinggi KNIL di Malang, aku erat dengan peperangan dan pemberontakan. Hampir setiap hari senapanku merenggut nyawa dan mortir-mortirku melululantahkan markas pemberontak. Itulah sebabnya kenapa aku memiliki rumah yang jauh dari pusat kota. Aku tak ingin Helena tahu banyak tentang pekerjaanku, aku tak mau melihatnya bersedih setelah kematian ibunya lima tahun silam. Beruntung sekarang aku sering melihatnya tersenyum dan tertawa, itu tak lepas dari kuda yang dimilikinya enam bulan terakhir yang mampu membilas sembilu pilu di hatinya.
Perlahan tapi pasti, senyum puteriku mengembang lebar. Ia semakin hari semakin bahagia meskipun aku menerapkan aturan agar dia pulang ke rumah maksimal jam 3 sore. Memang sengaja, agar tidak ada yang menggodanya. Kelak jika aku menemukan sinjo Belanda yang berpangkat, akan kunikahkan dengan puteriku. Sebelum aku menemukannya, biarlah dia bermain-main sendiri tanpa mengenal kaum adam mana pun di kota ini.
Awalnya aku tenang-tenang saja melihat ia bermain bersama kudanya. Namun lama kelamaan kekhawatiranku mulai membuncah. Semenjak kemunculan kuda ini, korban di rumah mulai berguguran satu per satu. Aku heran mengapa bisa demikian. Padahal kandang kuda juga dijaga oleh seorang body guard. Ah itu mungkin hanya kecurigaanku saja. Anehnya setiap aku mengalihkan rasa curigaku semakin aku penasaran untuk kembali mencurigai kuda itu. Kecurigaanku bahkan berujung pada kekhawatiran. Helena anakku memperlakukan kuda itu dengan sangat intim, ia memandikannya dan menciumi pipinya. Kuda ini memang sangat bersih dan sengaja aku menyewa dokter hewan khusus untuk merawatnya agar tidak terkena kuman, tapi tetap saja medis tidaklah cukup untuk menghapus kecurigaan yang mengulum jiwaku.
“Papi, Papi!!!” suara Helena mengagetkan lamunanku
Ia berteriak-teriak dari balik pintu ruang kerjaku.
“Kom op Helly, pintunya tak dikunci,” sahutku menimpali.
Seberkas wajah cantik muncul dari pintu yang terbuka perlahan. Ah puteri manisku, dia cantik seperti ibunya. Kulihat ia mengenakan gaun putih yang sering digunakannya saat ke gereja. Lengkap dengan sepatu kaca hak tinggi dan mahkota daun melingkar di kepalanya. Sungguh teramat cantik. Ia wanita sempurna yang kujaga dengan segenap hatiku. Ah tunggu dulu, hampir saja aku terhipnotis oleh kecantikannya hingga tak sadar kenapa ia berpenampilan seanggun ini padahal hari ini bukan hari Minggu dan tidak ada misa di gereja.
“Penampilanmu sangat menarik, Nak.Hendak ke mana kau hari ini?” tanyaku lirih.
Ia hanya tersenyum manja sembari berdiri di hadapanku. Pipinya merah pertanda malu. Ah apa yang sedang disembunyikannya. Tak pernah aku melihat dia tersipu malu seperti ini.
“Papi aku ingin menikah, Pi! Nikahkan aku sekarang juga boleh ya?”
Sungguh perkataan itu bagai halilintar di siang bolong. Apa aku tak salah dengar? Jangan-jangan yang di hadapanku ini bukan anakku melainkan jelmaan dari ibunya? Tidak! Bukan! Dia tetaplah anakku. Kakinya masih jelas menyentuh tanah.
“Kau! Kau mau menikah dengan siapa, Nak? Apa kau ingin mengajak bercanda ayahmu yang sudah tua ini?” tanyaku terbata-bata.
“Aku ingin menikah dengan Rawis , Ayah! Ia sudah menungguku di luar dan berpakaian putih sepertiku!”
“In Godsnam! Apa kau sehat, Nak!”
“Sehat, Ayah. Kalau aku tidak sehat tak mungkin aku hamil. Kemarin saat ayah kerja, aku sengaja telepon dokter kemari untuk periksa keadaanku dan ternyata aku hamil Ayah! Awalnya aku heran kenapa aku lama tak menstruasi dan perutku mual, ternyata benar aku hamil!” ucapnya dengan riang.
“Tak mungkin kau hamil! Kau tak pernah bergaul dengan lelaki! Siapa yang menghamilimu, Nak?”
“Rawis Ayah, dia juga lelaki, kan! Lelaki tampan yang berbulu indah!”
Kepalaku serasa pening bagaikan tertimpa jangkar Van der Wijk. Mana mungkin ini bisa terjadi? Sepanjang sejarah petualanganku sebagai mayoor, sudah berbagai daerah yang kutaklukan dan aku tak menemukan kasus seperti ini. Bahkan pelacur terkotor yang pernah kutiduri sekalipun tak akan melakukan hal konyol sebodoh itu. Mana mungkin aku menikahkan anakku dengan seekor kuda?
***
Malam ini rembulan berada di puncak peraduannya. Bintang gemintang bertengger ramah laksana malaikat pengawal purnama. Sinarnya begitu terang dan memesona. Saya pun melongok keluar untuk menghadapkan dahi saya sehadap dengan posisi rembulan. Cahaya rembulan menerangi dahi saya sehingga membuat seluruh tubuh saya menghangat. Perlahan tapi pasti, punggung saya mengeluarkan sayap yang teramat lebar dan tubuh saya jadi ringan seringan kapas. Di luar, saya melihat para penjaga terlelap dengan pulasnya sehingga memudahkan saya untuk keluar sebentar lagi.
Kini sayap saya mencuat dari punggung yang putih kekar ini. Semakin lama semakin melebar hingga mampu untuk dikepakkan. Dahi saya yang sedari tadi terkena caha bulan, mulai menyembulkan tanduk perak berkilauan. Saya pun menatap jendela kandang yang terbuka dan siap meluncur ke menara peraduan cinta paling tinggi.
Seperti purnama sebelumnya, saya berhasil keluar dari kandang saya dan terbang menuju lantai tiga rumah pemilik kandang saya. Sudah saya duga, di lantai tiga saat purnama seperti ini ada jendela yang tetap terbuka dan lampu kamar tetap menyala layaknya gerbang swargaloka.
“Cepat turun kemari, Rawis!” kata wanita yang memelihara saya.
Saya pun mendarat tepat di koridor kamar jendela itu kemudian masuk ke kamarnya
Wanita itu bukanlah wanita yang saya kategorikan sabar. Cekatan dia memeluk saya dengan erat. Jemari tangannya membelai rambut saya yang menjuntai ke belakang dari dahi ke punggung. Darah-darah dalam arteri serasa cepat mengalir sehingga saya pun serasa terbakar. Panasnya aliran darah saya membuat tubuh ini perlahan berubah setara dengannya. Kedua kaki saya di bagian depan berubah menjadi tangan dan kedua kaki saya di bagian belakang mulai berubah muncul jemarinya. Sayap saya mulai masuk lagi ke punggung yang sudah bisa menegak menjadi manusia seutuhnya. Bibir moncong saya pun memendek menjadi bibir tipis yang membuat saya menjadi lelaki seutuhnya.
“Sayang, kau sudah tak takut lagi padaku?” saya meyakinkan Helena.
“Tidak, Tampan. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga dan aku menginginkanmu malam ini!” ucapnya manja.
Malam begitu dingin. Semilir angin menerobos masuk merangsek memasuki ruang kamar sang puteri. Di dalamnya ada dua insan yang saling terjaga menikmati malam dengan caranya sendiri.
“Helena sayangku, kita telah menyatu atas nama cinta. Tunggulah sebulan lagi, kelak jika perutmu terasa mulai mual, itu pertanda bahwa benih cinta yang kutanam malam ini mulai tumbuh dalam rahimmu!”
“Iya Rawis, kelak jika memang itu terjadi aku akan mengatakan pada papi dan memintanya untuk menikahkan kita berdua sehingga kita dapat hidup selamanya sayang!”
“Tidak Helena, jangan! Aku yakin Papimu yang Mayoor KNIL itu tak mampu berdamai dengan kenyataan ini. Mana mungkin ia mau punya menantu seekor kuda? Meskipun demikian percayalah bahwa aku masih tetap mencintaimu dan selalu menemuimu saat purnama tiba!”
Ayam mulai berkokok, dari ufuk timur saya melihat matahari mulai memberkaskan sekelumit sinarnya. Itu pertanda bahwa saya harus berubah kembali menjadi kuda bersayap dan lompat dari jendela kamar Helena untuk masuk ke kandang di halaman belakang. Sebelum saya benar benar lompat, saya memberikannya sebungkus serbuk.
“Seperti biasa, Sayang, campurkan serbuk ini pada setiap makan malam tamu-tamu Papimu. Semakin kau taat padaku, semakin aku menyayangimu Helena” ucap saya pada Helena. Ia mengangguk paham.
***
Mayoor Van Marwick sangat geram mendengar pengakuan anaknya. Wajahnya merah menyala. Dahinya mengernyit berkumpul jadi satu membentuk panah ke arah hidung teramat mancung. Nafasnya mulai mendegus keras. Ia laksana banteng yang siap menyerunduk kain merah krimzi.
Tak mau berdiam diri, ia lalu mengambil senapan laras panjang yang terpampang di dinding barat kamarnya. Melihat hal itu, Helena berlari keluar mendobrak pintu rumah. Van Marwijk melangkah tegap ke kandang kuda. Menyibak rerumputan, menghalau hembusan angin yang menerpanya. Semua ajudan tunduk tak berani tatap muka sang mayoor. Di belakangnya ada Helena, berlari meraung-raung menyuruh papinya berhenti. Langkah jenderal semakin mantap tak gentar hingga tepat berada di depan pintu kandang kuda.
“Masukklah, Tuan! Tak dikunci pintunya,” ujar seorang lelaki dengan suara basah.
Mata Van Marwijk semakin merah jahanam, ia langsung memopor pintu kandang. Setelah pintu benar-benar terbuka, diberondongkannya peluru ke dalam kandang secara serampangan. Memang benar, amarah membutakan akal. Setelah puas kesetanan, ia menghela keringat di dahi sembari berharap ada seekor kuda bermandi darah. Setelah semua serbuk mesiu menghilang dari pandanganya, Van Marwijk sadar bahwa semua pelurunya hanya melobangi dinding-dinding kandang.
“Aku di sini, Tuan,” ucap seorang lelaki yang melompat dari atap kandang sembari menendang kepala Van Marwijk hingga jatuh tersungkur. Senapan pun lepas dari tangan Van Marwijk dan disahut cepat oleh pemuda tangkas.
“Siapa kau sebenarnya?” ujar Van Marwijk.
“Aku adalah Rawis, kuda yang kau pelihara selama ini!” pemuda tersenyum simpul sambil mengarahkan moncong senapan ke arah kepala Van Marwijk.
“Mana mungkin seekor kuda bisa menjadi manusia?” tanya Van Marwijk.
“Mana mungkin pula seluruh tanah di kota ini hingga pelosok desa dikuasai oleh kaummu? Namun lihat! Tak ada yang tak mungkin bukan?!” timpal Rawis.
Pemuda itu mendekatkan langkah sambil mengarahkan moncong senapan pada Van Marwijk.
“Tahukah kau peristiwa pemberontakan di stasiun kota setahun silam, saat itu ratusan mortir dilempar oleh anak buahmu secara serampangan? Anak dan isteriku pun terkena getahnya sehingga aku hidup menduda. Saat itu, aku menjadi gila dan berlari tak tahu arah hingga aku tiba di bawah kaki Gunung Kawi. Di sana aku bertemu seekor kuda putih dan bertapa di gua yang disinggahinya. Ragaku dan kuda itu menyatu, aku kini memiliki kekebalan. Kau pasti tak menyangka semua ini terjadi kan Van Marwijk? Di negerimu, hukum fisika dan ilmu terbaik sekalipun bahkan tak mampu membuktikan kejadian ini! Hai Van Marwijk ingat kau di mana? Kau berada di tanahku!”
Van Marwijk masih tersungkur dan mengepalkan kedua tangganya ke tanah. Ia benar-benar tak habis pikir dengan semua takhayul yang diucapkan masyarakat setempat nyatanya benar adanya.
“Sekarang apa maumu wahai pemuda kuda? Apa kau mau menikahi puteriku?” ucap Van Marwijk dengan nada dalam.
“Van Marwijk kau begitu bodoh! Mana mungkin aku yang baru saja ditinggalkan isteri dan anakku langsung mencari isteri baru. Puterimu memang cantik tak terkira, namun tahukah kau bahwa ia hanya kuperdaya untuk menghancurkanmu dan tamu-tamu terbaikmu!” ucap Rawis sembari menekan pelatuk senapan di tangannya.
Psss,
Hanya bisikan angin yang keluar dari moncong senapan Rawis. Di sisi lain, senyum tipis mulai tersungging dari mulut Van Marwijk.
“Jangan panggil aku mayoor jika aku tak paham seni bertarung, Nak!” ucap Van Marwijk sambil mengeluarkan sepucuk pistol dari saku celananya. Nama Maretha terukir jelas di ujung pistol pamungkas milik sang mayoor.
“Biar Maretha isteriku yang menghukummu karena kau telah melukai perasaan puterinya,” kini Van Marwijk yang mengarahkan moncong pistolnya ke arah dada Rawis. Rawis mulai terdesak.
Lelaki jelmaan kuda itu tak mau menanggung malu, ia berlari ke arah Van Marwijk hendak memukul sang mayoor. Melihat hal nekat itu, Van Marwijk tak mau mengambil pusing. Tangan kanannya telah mengeras menggenggam senapan, bersiap menekan pelatuknya dan….
Dorrrrr!
Mata Van Marwijk terbelalak. Wajahnya penuh dengan semburat darah. Setelah diusap wajahnya, ia tahu bahwa darah yang muncrat ke wajah itu bukanlah darah lawannya, bukan juga darahnya sendiri.
Sungguh Van Marwijk terguncang hatinya, ia sadar bahwa darah yang baru saja diusapnya adalah puterinya yang kini terbaring di pelukan lelaki yang sangat dicintai oleh wanita itu.
“Rawis, aku juga isterimu, kan? Isteri yang kelak akan melahirkan anakmu,” ucap Helena dengan menahan sakit di dadanya yang kini tersarang sebutir peluru.
Betapa terkejutnya Rawis bahwa cinta Helena begitu tulus sehingga ia rela melakukan semua ini. Belum sempat Rawis menjawab pertanyaan Helena, wanita manis itu telah lemas berpasrah melepaskan nyawa pada pelukan lelaki yang benar-benar dicintainya.
Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan Harapan III Kompetisi Penulisan Cerpen Majalah Komunikasi 2016