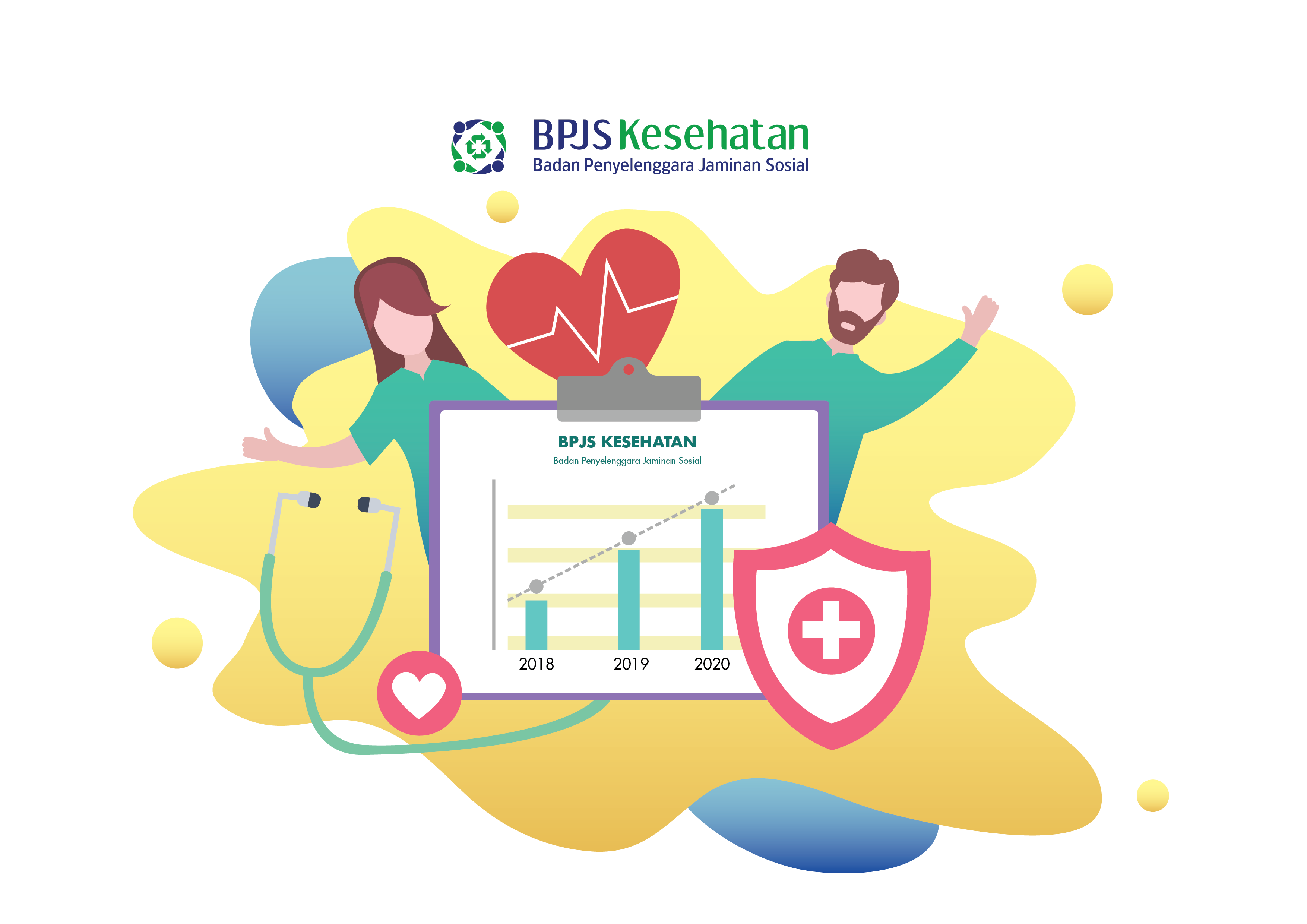Beberapa waktu ini tengah gencar diberitakan mengenai kenaikan premi BPJS, baik untuk kelas satu, kelas dua, maupun kelas tiga. Faktanya, masalah defisit BPJS kesehatan memang masih menjadi polemik hingga saat ini. Lalu apakah kebijakan tersebut dapat menjadi solusi dari peliknya permasalahan BPJS? Jika melihat ke belakang, defisit atau kerugian BPJS memang tergolong terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2014 hingga 2017. Berawal dari defisit yang dialami sebesar Rp3,3 triliun pada tahun 2014, dilanjutkan pada tahun 2015 sebesar Rp5,7 triliun, tahun 2016 sebesar Rp9,7 triliun, dan tahun 2017 sebanyak Rp9,75 triliun. Hingga sempat mengalami sedikit penurunan defisit pada tahun 2018 menjadi Rp9,1 triliun. Diperkirakan, BPJS Kesehatan akan kembali mengalami defisit sebesar Rp28 triliun pada tahun 2019 ini.
Memang BPJS sempat mengalami penurunan defisit dari Tahun 2017 ke 2018, akan tetapi penurunan tersebut tidak cukup signifikan meskipun telah ada sumbangsih dana alokasi dari cukai rokok. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI bahwa BPJS Kesehatan mendapatkan suntikan dana dari cukai hasil tembakau sebesar Rp1,48 triliun. Namun, hanya beberapa daerah yang bisa mendapatkan suntikan dana tersebut, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Tentunya hal ini sekaligus membuktikan bahwa sumbangan dana dari cukai rokok pun masih belum cukup efektif untuk mengatasi masalah ini. Ketidakefektivan penggunaan dana cukai rokok juga dilatarbelakangi oleh ketimpangan antardaerah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua daerah memperoleh dana bagi hasil cukai tembakau untuk dialokasiakan ke pelayanan kesehatan di daerah masing-masing.
Selain itu, menurut Staf Ahli Menteri bidang Hukum Kesehatan, Tritarayati, ada sekitar 70% biaya yang tersedot oleh penyakit akibat paparan asap rokok seperti penyakit jantung, ginjal, dan stroke. Hal diperkuat oleh pendapat Soewarta Kosen dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan bahwa kerugian ekonomi untuk biaya kesehatan mencapai Rp596,61 triliun di tahun 2015. Sementara pada laporan penelitian yang dilansir Kemenkes pada tahun yang sama menunjukkan bahwa perkiraan total belanja rokok oleh perokok aktif mencapai 36,3%. Kemudian total jumlah perokok dikali Rp3.099.600, dari belanja rokok per kapita dalam sebulan sebesar Rp258.500, maka hasilnya menyentuh angka Rp208,8 triliun rupiah. Tentu angka tersebut memang tidak sedikit, akan tetapi masih belum dapat menutupi kebutuhan biaya kesehatan yang diakibatkan kebiasaan mengonsumsi rokok.
Di sisi lain, apabila produksi rokok dihentikan juga akan menjadi dilema tersendiri, terlebih lagi mengingat bahwa saat ini rokok berperan sebagai penyumbang devisa terbanyak. Pada tahun 2018 lalu saja cukai rokok menyumbang sebesar Rp153 triliun untuk kas negara dan belum ada yang dapat menandingi pemasukan yang disumbang dari sektor rokok. Belum lagi, rokok juga sangat berperan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Pada akhirnya setiap kebijakan yang akan atau sedang diambil akan mendatangkan sisi negatif dan positif masing-masing, termasuk dalam hal kenaikan premi BPJS. Tentunya keputusan tersebut diambil oleh pemerintah tentunya dengan pertimbangan agar defisit BPJS tidak semakin membengkak lagi.
Di lain kasus, kesadaran masyarakat akan pentingnya BPJS masih cukup rendah, sehingga mereka enggan membayar iuran rutin karena merasa tidak sakit. Belum lagi ada juga masyarakat yang baru mau mendaftar BPJS setelah penyakitnya sudah cukup parah (ketika sudah mulai mengeluarkan banyak dana). Jika demikian, bukan tidak mungkin bahwa defisit yang diderita BPJS Kesehatan akan terus berkelanjutan. Pada akhirnya pemerintah hanya bisa berusaha memutar otak untuk menutupi defisit BPJS dengan cara menaikan premi peserta. Harapan pemerintah dengan adanya kebijakan tersebut pada tahun 2020 BPJS Kesehatan sudah tidak mengalami defisit lagi. Rencana ini telah ditentukan dan sedang dalam proses menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Penerapan aturan ini diberlakukan mulai bulan Agustus 2019 untuk golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sedangkan untuk peserta golongan non Penerima Bantuan Iuran seperti Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai diberlakukan pada bulan September 2019. Rencana untuk peserta kelas satu yang sebelumnya membayar premi sebesar Rp80.000 rencananya akan naik menjadi Rp120.000. Kemudian untuk kelas dua yang semula Rp51.000 menjadi Rp80.000 dan kelas tiga yang awalnya Rp25.500 menjadi Rp42.000. Tentunya kebijakan ini juga memiliki sisi positif dan negatif. Sisi negatif dari kebijakan ini adalah kepesertaan BPJS Kesehatan yang mayoritas merupakan golongan PBI. Kenaikan jumlah peserta BPJS memang terus meningkat seiring waktu, bahkan pada awal tahun 2019 sudah mencapai 81,8%. Sayangnya, jumlah tersebut tidaklah seimbang antara peserta PBI dan non PBI. Bahkan dapat dikatakan bahwa peserta PBI dan non PBI memiliki perbandingan sebesar 9:1. Dari sini dapat dilihat bahwa memang benar bahwa kepesertaan BPJS terus bertambah, akan tetapi apabila jumlah peserta PBI lebih banyak daripada peserta non PBI maka akan sama saja tanggungan pemerintah juga akan semakin membengkak. Terlebih, jumlah kepesertaan ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang layak.
Sejak pemerintah mengeluarkan Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan sudah bertransformasi menjadi tidak gratis lagi. Pelayanan kesehatan untuk rawat jalan saja dikenai biaya Rp20.000- Rp10.000, tergantung tipe rumah sakit. Belum lagi frekuensi kunjungan yang dibatasi maksimal 20 kali dalam jangka waktu tiga bulan dan biaya maksimal hanya Rp350.000. Sementara untuk rawat inap dikenai biaya sebesar 10% dari total biaya yang ditanggung peserta dengan biaya maksimal Rp30.000.000.
Semoga dengan adanya kebijakan kenaikan premi BPJS dapat menjadi jalan keluar bagi permasalah BPJS Kesehatan yang belum menemui titik terang. Selain itu juga semoga kenaikan premi ini juga tidak menjadi bumerang bagi pemerintah terkait dengan banyaknya peserta PBI. Jika ada pertanyaan “apakah solusi ini dapat benarbenar menjadi jalan keluar dari masalah yang hampir tak ada ujungnya ini?”, tentu belum ada yang bisa menjawab hingga kebijakan ini diimplementasikan dan dievaluasi. Bagaimana kebijakan ini akan berjalan tentu juga bergantung pada kerja sama seluruh pihak karena pada dasarnya perputaran dana BPJS kesehatan menggunakan prinsip gotong royong. Maka dari itu diperlukan partisipasi yang sangat besar dari masyarakat, khususnya para peserta. Tentu juga harus ada perubahan pengetahuan atau pola pikir (mindset) dan perubahan perilaku yang harus diimplementasikan kepada masyarakat Indonesia.
Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya kita bersikap kritis dan tidak lagi bersikap apatis. Tak jarang masih ada mahasiswa yang belum mengerti apakah ia sudah mendaftar BPJS kesehatan ataukah belum. Tentunya hal tersebut cukup ironis, padahal mahasiswa merupakan salah satu komponen masyarakat yang diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan perilaku karena tingkat pendidikan mereka yang cukup tinggi. Mahasiswa tentunya harus turut memahami program atau kebijakan pemerintah baik yang akan dicanangkan atau yang sudah diterapkan. Jika demikian, mahasiswa baru dapat menjadi pelopor adanya perubahan perilaku. Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan pemuda selaku mahasiswa adalah dengan membantu melakukan promosi kesehatan menggunakan metode loss frame or gain frame (edukasi tentang keuntungan dan kerugian) dengan tujuan untuk mengubah persepsi risiko, kesadaran, dan kepercayaan kesehatan.
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Juara I Penulisan Opini Majalah Komunikasi