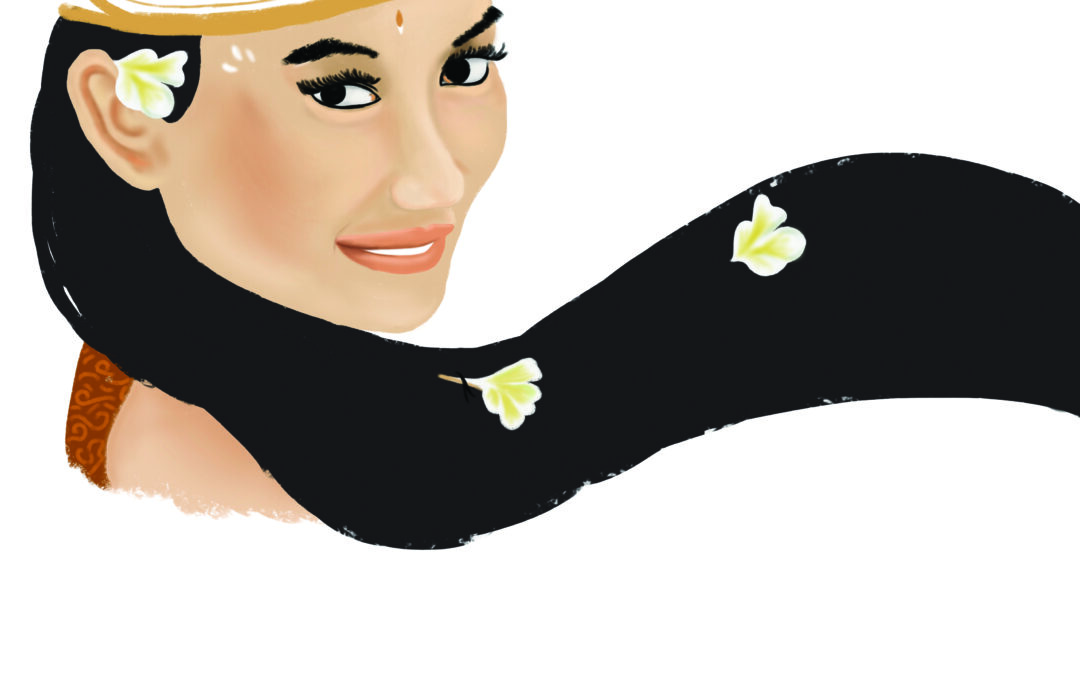—Aham bhumim adadam aryay, aham vrsthim dasuse martyaya1—
Sudah pukul lima sore, lebih lima belas menit. Matahari sudah tak nampak lagi. Beberapa orang berbondong menuju pura untuk melaksanakan Puja Tri Sandhya. Beberapa ada yang sudah mengapit kelopak kamboja diantara jemarinya. Menangkupkan kedua tangannya, kemudian berlangsung lah sembahyang mereka.
Ujung sebuah penantianmu berakhir pada sesosok perempuan dengan mengenakan kebaya brokat berwarna merah bata. Seperti biasanya, ia mengenakan pusung gonjer2 yang telah diselipi beberapa bunga kenanga yang menguning. Langkahnya amat anggun dalam sinjang3disertai paras ayunya yang kuning langsat. Bija4 pun masih menempel di dahinya, antara dua alisnya yang hampir bertaut.
Entah keberapa kalinya kau duduk berlama-lama diantara rerimbunan daun meluh5 seraya meniti orang-orang bergegas menuju ke pura untuk bersembahyang. Kadangkala kau tak segan memungut kelopak-kelopak meluh yang mekar dan memutih. Duduk berlama-lama sambil dikawani pènjor6 yang tinggi menjulang seperti hendak mencakar angkasa. Tak jarang kau mendapatkan senyum simpul dari mereka yang datang sambil sedikit membungkukkan badan.
Kau seperti membuang waktumu saja. Menghabiskan bermenit-menit untuk sekedar menunggu.
Hatimu tiba-tiba berdesir, menghitung langkah gadis yang kau nanti semakin mendekat ke arahmu. Kau berusaha mendamaikan hatimu yang gugup dan berdebar-debar. Sementara perempuan itu melangkah membawa canang sari7disertai perbincangan yang amat renyah bersama perempuan-perempuan lainnya yang berjalan beriringan dengan perempuan yang selama ini kau ketahui bernama Kinanti.
Ni Putu Ayu Kinanti. Perempuan yang terhitung banyak dielu-elukan banyak pemuda di Kintamani. Lembut lisannya menyihir banyak lelaki sehingga tak sedikit dari mereka yang ingin mendekatinya, termasuk kau. Kau tak menemukan banyak alasan untuk tidak memperhatikan perempuan itu. Kau juga tak dapat memungkiri bahwa malam-malammu selalu terganggu atas parasnya yang begitu membayangimu. Belum lagi, tatapan matanya yang meneduhkan hati. Kadangkala kau hampir dibuat linglung tersebab perempuan itu yang selalu menghantuimu. Kinanti benar-benar merasuk dalam hidupmu.
Tiada sesiapa-pun tahu bahwa kau seringkali membuntuti Kinanti. Memandang parasnya dalam jala retinamu dari kejauhan, bersembunyi. Kau mengingat-ingat lagi untuk kali pertama kau bertatap muka dengan Kinanti.
***
Burung prenjak berkicau begitu nyaring. Cenggeret nampaknya banyak bersembunyi di balik daun bambu. Atmosfer yang berbeda dari kehidupan yang biasa kau jalani. Kau menghirup dalam-dalam lagi pagi ini, seraya merasakan kedamaian yang tak terkira seperti tujuh hari yang telah berlalu. Tidak terhitung bagaimana lelah yang kau dera. Semua itu telah berbayar dengan keindahan alam yang begitu mempesona.
Kau berdiri di bibir jendela, menyibak tirai dan membiarkan cahaya matahari menerobos masuk menghangatkan tubuhmu.
“Rahajeng Enjing.” Kata Mak Naeh mengucapkan selamat pagi dengan logat Bali-nya yang amat kental. Mak Naeh—istri Nyoman Dauh pemilik rumah yang saat ini menampungmu—membawakan tampah berisi sepiring ubi kayu yang sudah direbus serta kopi hitam yang rupanya bercampur dengan cengkeh aromanya memenuhi ruangan.
Kau berbalik badan, mencari asal suara lantas menimpali dengan senyum.
“Suksma.” Katamu, berterimakasih dalam dialek Bali.
“Sarapan dahulu.” Tambah Mak Naeh meletakkan tampah di meja dekat udeng8 yang melingkar di kepalamu saat kau meliput upacara Mewidhi Widana9 kemarin malam di kediaman seorang Ida Peranda10.
“Bila butuh sesuatu, panggil saja. Mak ada di wingking11.” Ujar Mak Naeh sambil berpamit diri menuju pawon—dapur.
“Iya Mak. Suksma.” Jawabmu lagi memakai dialek Bali.
Kau kembali berdiri di bibir jendela. Kali ini kau melempar pandang pada perempuan-perempuan Bali yang mengenakan kebaya dengan membawa sesajen berupa buah-buahan yang hendak dibawa ke Bali. Ada pula lelaki paruh baya yang mengayuh onthelnya dengan membawa daun-daun jeliring12.
Hari ini kau akan ikut Kadek Wibisono-kawanmu, mengunjungi kawanmu yang lain di Kintamani. Kalian sepakat untuk bertemu di Pura Ulun Danun Batur yang letaknya di Desa Kalanganyar di sebelah Timur jalan raya Denpasar, Singaraja.
***
Aham bhumim adadam aryaya.
aham vrsthim dasuse martyaya,
aham apo anayam vavasana
mama devaso anu ketam ayam13
Pertama kali kau menapakkan kaki di halaman pura, kau merasakan atmosfer religius yang begitu kental. Alangkah damai. Terlihat di matamu beberapa perempuan yang sedang menyusun bebungaan di atas canang sari. Berderet-deret canangsari telah siap digunakan untuk sembahyang.
Betapa terperanjat hatimu ketika sepasang matamu menatap seorang perempuan yang duduk seorang diri sambil menata canang sari yang telah penuh. Kau mengamatinya diam-diam.
“Mengapa kau letakkan bunga merah itu kau letakkan disisi bunga putih? Bukankah kau dapat menyusunnya berdekatan dengan bunga yang berwarna kuning?” tanyamu mendekati salah satu perempuan yang duduk bersimpuh sambil memilah-milah kuntum bunga yang masih segar.
“Bunga berwarna Putih disusun di Timur sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Iswara.” Jawabnya dengan santun disertai satu senyuman yang sungguh legit. Kau tak begitu faham, namun kau masih ingin mendengar suaranya. Kau bertanya lagi.
“Lantas mengapa kau letakkan bunga berwarna biru menghadap ke utara?”
“Bunga berwarna Biru atau Hijau disusun di Utara sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Wisnu. Bunga berwarna Merah disusun di Selatan sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Brahma. Bunga berwarna Kuning disusun di Barat sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Mahadewa.” Kau terkesima. Perempuan itu menjawab dengan runut. Kau menganngguk-anggukkan kepalamu tanda faham. Tanda mengetahui, lebih tepatnya.
Tiba-tiba Kadek datang menepuk pundakmu dari belakang. “Ngudiang? Uli semeng tiyang ngantosang14.” Kau hanya menyambut kedatangan Kadek dengan senyuman yang bermakna tak mengerti atas ucapannya yang baru saja.
“Ampura15. Ini kawan saya.” Ucap Kadek pada perempuan yang sempat kau ajak bicara. Kau berucap syukur seketika lalu mengulurkan tangan untuk memperkenalkan diri. Kau terlalu naif untuk mengawali percakapan dengan menanyakan nama dan sebagainya.
“Kinanti.” Katanya dengan santun sambil menangkupkan kedua tangannya yang lentik.
“Maaf Kinati bila kehadiran kawan saya mengusikmu.” Kadek meminta maaf lagi. Kemudian undur diri. Ingin hati bercakap-cakap lebih lama. Namun rupanya masa tak begitu mengizinkan.
Kau mengekor di belakang Kadek. Sambil sesekali berbalik badan, kembali menatap perempuan yang mampu menyita perhatianmu.
“Kinanti itu siapa, Dek?” tanyamu pada Kadek sambil mengikuti langkahnya.
“Tiyang sing nawang?16 Dia sudah ada yang meminang. Calon suaminya berkasta Ksahtriya. Tak boleh lagi kau mendekatinya. Apalagi kau berani mengajaknya bicara.” Itu bukan jawaban yang tepat atas pertanyaan yang sudah kau lontarkan.
“Apa salahnya? Hanya berbicara biasa.” Kau memberikan pembelaan.
Kadek menghela nafas. Kemudian, ia membeberkan penjelasan panjang lebar sepanjang jalan. Sayangnya kau tak begitu menggubrisnya. Sesekali saja kau menoleh ke arah Kadek sambil berpura-pura menyimak.
Satu yang tak dapat kau tutupi. Bahwa kau jatuh hati pada perempuan itu. Perempuan penyusun bunga pada canangsari. Perempuan Kintamani.
Aduhai, Hyang Widhi. Sihir apa yang telah Kinanti kirimkan pada hamba? Kau seperti memanjatkan doa kepada Tuhannya Kinanti.
***
Kau kembali tersadar ketika langkah perempuan itu benar-benar semakin mendekatimu. Kau serta merta membuyarkan lamunan panjangmu. Kau berusaha untuk tidak gugup. Namun kau tahu, bahwa kau tak begitu mahir menyembunyikan mimik wajahmu itu. Mau tak mau, kau harus bersitatap dengan Kinanti. Ah, tidak juga. Kau berbalik badan. Kinanti melewatimu.
Kau seperti mengutuk dirimu sendiri yang terlalu tak mampu berucap sepatah katapun ketika niat hatimu ingin menyatakan sesuatu yang harusnya dikatakan.
Kau tetaplah kau. Putu Wijaya yang senantiasa setia menanti senja yang rubuh ditimbun dedaunan meluh. Kau akan berkawan senja ketika ia kembali mencapai ranumnya. Sudah menjadi hal yang biasa bila orang-orang yang gegas menuju pura untuk ber-Puja Tri Sandhya, menemui lelaki dengan mengenakan udheng sambil duduk di muka pura, yaitu kau.
Barangkali cukup dengan dilabuhkannya senyum legitnya saja, hatimu telah bersorak-sorai bahagia. Betapa menyedihkannya dirimu yang hanya mampu menatapnya ketika kau dan dia begitu berjarak.
Esok dan seterusnya akan selalu begitu. Esok dan seterusnya mungkin akan menjadi cerita yang sama. Esok dan seterusnya akan menorehkan kisah yang tidak berbeda, bila Kau masih tak mau mengalahkan hatimu untuk menyapa perempuan itu.
Kau tetap menjadi Putu Wijaya yang setia menanti kedatangan perempuan Kintamani penyusun bunga di atas canangsari, bernama Kinanti.
Penulis adalah mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Cerpen ini Juara Harapan III kategori Cerpen Kompetisi Penulisan Rubrik Majalah Komunikasi 2015
1. Rgveda IV.26.2. artinya Aku anugerahkan bumi ini kepada orang yang mulia. Aku turunkan hujan yang bermanfaat bagi semua makhluk.
2. Sanggul untuk perempuan yang belum menikah.
3. Kain lapis sebelum mengenakan pakaian Agung.
4. Bija atau wija adalah biji beras yang telah dicuci dengan air bersih atau air cendana.
5. Melati.
6. Hiasan dari bambu yang dililiti daun kelapa muda (janur).
7. Canangsari adalah sesaji yang berisi buah dan bunga, beralaskan “ceper” (berbentuk segi empat) yang menjadi simbol kekuatan “Ardha
Candra” (bulan). Canangsari biasa digunakan untuk upacara sembahyang sehari-hari dan upacara keagamaan lainnya.
8. Penutup kepala di Bali untuk kaum laki-laki.
9. Salah satu dari serangkaian upacara pernikahan adat Bali.
10. Yang memimpin acara Mewidhi Widana.
11. Belakang
12. Janur
13. Aku anugerahkan bumi ini kepada orang yang mulia. Aku turunkan hujan yang bermanfaat bagi semua makhluk. Aku alirkan terus
gemuruhnya air dan hukum alam yang patut pada kehendak-Ku. (Rgveda IV.26.2).
14. Ngapain? Sejak pagi saya menunggu.
15. Maaf Mas.
16. Kamu tidak tahu?