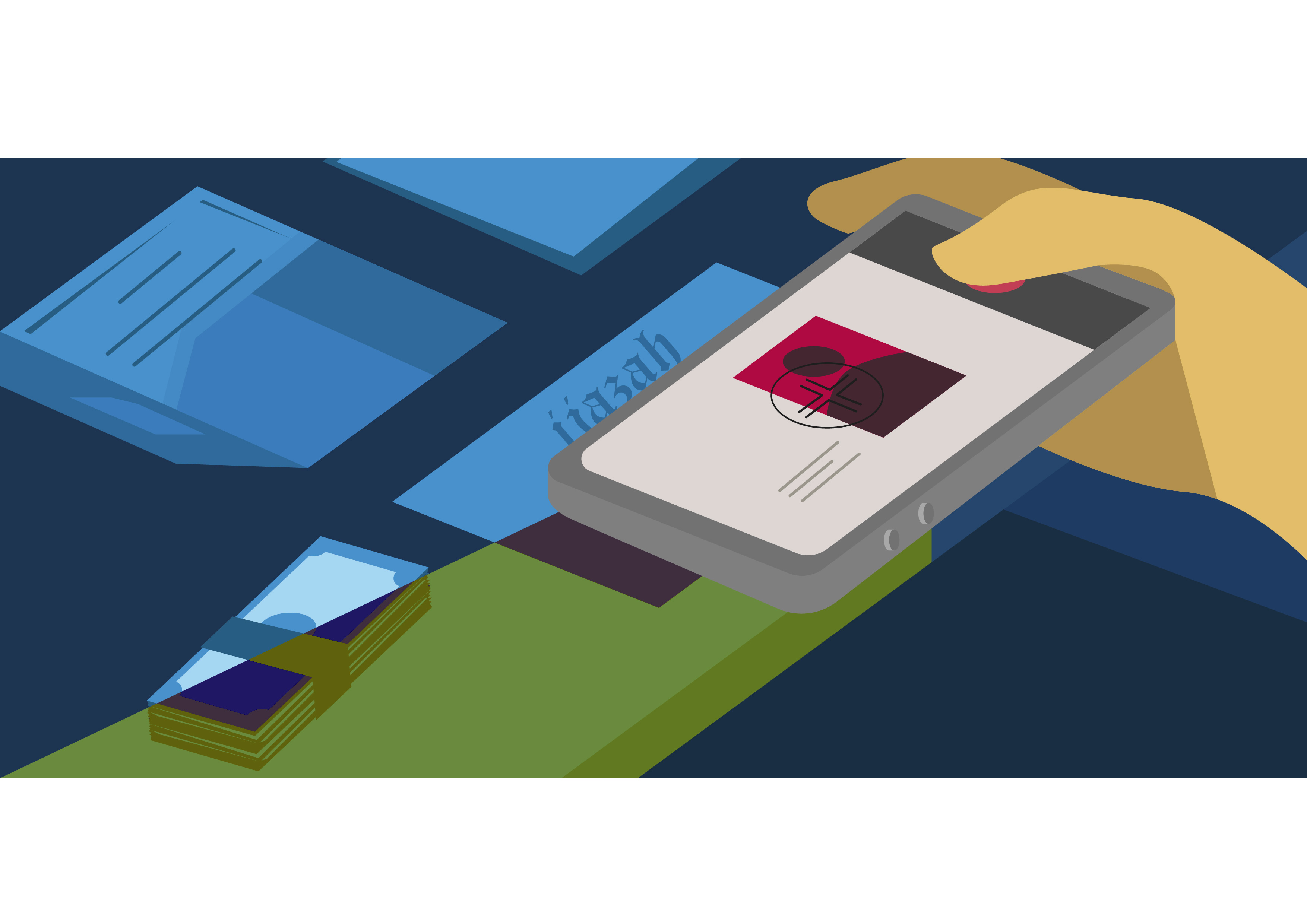Koridor sebuah gedung yang kerapkali dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan itu tampak sepi. Biasanya, pukul sembilan saja sudah ramai. Ada yang duduk berjajar di kursi besi yang telah disediakan, ada yang berdiri mematung sambil berkacak pinggang atau melipat tangan, ada yang memencat-mencat ponsel (mengetik pesan atau nomor HP), dan ada pula yang mondar-mandir seperti orang cemas. Kali ini, memang tidak biasa. Ganjil.

Rupa-rupanya, menurut penuturan seorang petugas kebersihan, sejak dua hari lalu memang sepi pengunjung. Kalau pun ada, satu atau dua orang saja sehingga pukul 15.00 mereka sudah harus tutup dan pulang. Otomatis sudah tidak ada kegiatan apa-apa lagi. Aku yang bekerja sebagai jurnalis –nyaris seperti intel atau anggota BIN/CIA– dirundung rasa penasaran. Benar-benar ingin tahu hal ihwal apa yang menyebabkan gedung ala-ala Belanda itu sepi. Muncul pula beragam pertanyaan yang kian menyeruak membuat sesak. Curiga bercampur heran. Penasaran sekali.
Kuputuskan berkunjung ke tempat itu dua hari lagi untuk melihat perkembangan apa yang terjadi. Hitung-hitung sekaligus mencari angin segar sebab baru kali ini aku mendapat mandat amat ringan dari pimred. Hanya meliput aktivitas di gedung putih itu. Biasanya aku harus terjun ke tempat-tempat yang sangat ekstrem demi mendapatkan hot news. Tidak apalah, asalkan bulan depan, sesuai janji Pak Bos, gajiku naik sepuluh persen. Kuturuti saja titah beliau dengan penuh loyalitas.
Benar sungguh, sepagi ini, kulirik arloji bermerek Alba di pergelangan tangan kiriku masih menunjuk pukul 07.09. Aku sudah berada di depan gedung putih bersama seorang satpam berwajah garang. Beliau menyeletuk saat berhadapan denganku.
“Hei, cari siapa? Pagi-pagi kok sudah ke sini? Kantor saja belum buka.”
“Oh, saya mau ada perlu, Pak. Saya calon klien di kantor ini. Perkenalkan, saya Ratna,” aku mengulurkan tangan.
“Kamu apa tidak tahu kantor ini buka pukul 08.30?”
“Tentu tidak, Pak. Saya khawatir jika nanti mengantre sehingga harus datang lebih awal.”
“Hmmm, begitu, ya? Tunggu saja di depan pos satpam itu.”
Aku bergegas duduk di kursi yang telah disediakan tepat di bawah jendela pos sambil memerhatikan sekeliling. Kelang beberapa menit, sebuah mobil sedan biru dongker memasuki halaman gedung. Tampak seorang pria bersafari hijau toska turun menenteng tas, lalu terburu-buru masuk. Aku bertanya kepada satpam siapa pria itu.
“Pak, siapa ya bapak muda itu?”
“Oh, itu bos di kantor ini. Beliau memang awal.”
“Pak, boleh tanya-tanya lagi?”
“Apa itu?”
“Klien di kantor ini dari mana saja, ya?”
“Wah, hampir seluruh kota besar di Indonesia. Kamu sendiri dari mana dan untuk keperluan apa ke sini?”
“Saya dari Tangerang, biasa Pak, mau nyaleg.”
Satpam itu manggut-manggut tanda paham. Padahal, aku berbohong demi melancarkan aksi. Mana mungkin tampang sepertiku mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tidak terasa, hampir sejam aku duduk. Aku terkesima melihat seorang perempuan yang datang. Mungkin saja dia tamu, mungkin juga pekerja. Perempuan itu bersanggul menyerupai pramugari, memakai rok mini, kemeja pendek, dan setelan rompi. Make up tebal. Sepatu heels hitam. Kulitnya putih bersih. Berjalan berlenggok-lenggok. Dia mengendarai ayla merah, senada dengan warna tas mahalnya.
”Perempuan ini memegang jabatan apa, ya?” gumamku.
Tiba-tiba satpam di sebelahku membuyarkan fokus tentang perempuan cantik tadi, “Sudah, masuk saja! Daripada nanti ngantre!” perintah satpam.
“Baik, Pak.”
Aku memasuki pintu utama kantor yang lebih mirip seperti guest house. Seorang office boy mempersilakan duduk di sofa biru safir yang menghadap ke meja resepsionis. Padahal, meja resepsionis belum dihuni oleh seorang pun. Tiba-tiba perempuan sosialita tadi menghampiri.
“Ada perlu apa, Mbak? Mari ikut saya ke ruangan,” ajaknya.
“Saya mau membuat ijazah sarjana, Mbak.” Aku berdiri sembari megikuti kakinya yang jenjang melangkah. Kami masuk ke ruangan elite ber-AC, yang dindingnya berwarna kuning gading dilengkapi dengan kulkas dan hiasan lainnya.
“Duduklah!”
Aku duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja hitam bertapak rajutan kuning. Perempuan itu memutar-mutarkan kursinya. Santai sekali. Aku menepis rasa canggung agar tidak dicurigai.
“Kalau boleh tahu ijazah sarjananya untuk apa, Mbak?”
“Untuk nyaleg, Mbak. Maklum saya tak berijazah S-1. Saya pernah kuliah, tetapi cuma setahun. Lalu, keluar karena tertarik bekerja. Oh ya, selain menyediakan jasa pembuatan ijazah palsu, di kantor ini melayani apa lagi?”
“Oh, banyak. Ada pemalsuan paspor, KTP, akta tanah, KK, bahkan buku nikah. Mbak pernah mengikuti berita tentang Gayus Tambunan, kan? Nah, kami bisa membuat paspor seperti dia. Memalsukan nama sehingga seseorang bisa pergi ke mana saja,” jelas perempuan yang kuketahui lewat tulisan di atas mejanya bernama Renny.
“Oh, begitu. Apa tidak pernah ketahuan?”
“Selama hampir empat tahun kami beroperasi tidak pernah ketahuan. Semua mulus, hanya saja beberapa hari ini sepi karena tidak musim lowongan pekerjaan dan wisata ke luar negeri. Namun, Mbak orang pertama pada bulan ini yang datang untuk keperluan nyaleg.”
Setelah berceloteh panjang lebar sampai disuguhkan sebotol minuman ringan rasa jeruk florida dan sepotong donat, aku pun berpamitan. Akan tetapi, tidak asal pamit. Di kantor itu sudah ditetapkan bahwa siapa pun yang jadi atau tidak menggunakan jasa mereka, harus membayar uang panjar. Aku terpaksa merogoh dompet dan menyerahkan tiga lembar uang kertas merah sebagai jaminan. Kupikir tidak masalah sebab aku telah mendapatkan informasi penting. Semua pengakuan Renny sudah kurekam menggunakan HP yang kusimpan dalam saku celana. Tiga hari lagi aku diminta kembali sambil menyerahkan pas foto warna dan nilai di ijazah yang kuinginkan. Mereka tidak mau meminta secara online karena khawatir akan disadap.
Sesuai hari yang ditetapkan, aku kembali ke kantor putih tempat para mafia dokumen itu bersemayam. Kali ini misiku ialah bisa bertemu langsung dengan bosnya untuk mengorek informasi siapa saja nama-nama klien yang pernah menggunakan jasa kotor mereka. Kasihan rakyat bila terus dibohongi. Rasanya tidak pantas dipimpin oleh orang-orang pendusta yang bermental instan. Tidak mau berlelah sekolah, tetapi bergelar macam-macam demi bisa memimpin.
Sama seperti beberapa hari lalu, kantor yang tidak bernama itu, sepi. Padahal, aku datang sekitar pukul 10.30. Hanya terlihat dua motor dan tiga mobil terparkir. Kuberanikan masuk. Kali ini ada seorang perempuan muda berseragam batik berdiri di balik meja resepsionis sambil menyapa.
“Selamat pagi, Mbak. Sudah pernah ke sini?”
“Sudah, Mbak. Saya cuma mau mengantar pas foto.”
“Oke, tunggu saja.”
Saat itu juga kulihat lelaki parlente yang pernah kulihat bersama sedannya melewatiku. Entah mengapa muncul niat untuk mengikutinya. Aku pun berpura-pura hendak ke toilet. Aku yang sudah biasa menguntit atau mengikuti –orang tidak pernah gagal– terus saja diam-diam berada di belakang lelaki itu. Sampailah di sebuah ruangan pribadinya di lantai dua. Lelaki itu membuka pintu ruangan. Aku bersembunyi di dekat tangga tepat di balik lemari. Tidak lama kemudian, lelaki itu keluar menuruni anak tangga. Setelah dia lenyap, aku segera masuk ke ruangannya yang tidak dikunci.
Di ruangan itu kuamati seluruh isi, bahkan kufoto. Aku juga menemukan tumpukan berkas. Kubuka dengan cepat. Ternyata isinya nama, foto, nomor HP, alamat, dan jumlah nominal yang harus dibayar oleh para klien. Ada kepala daerah, kepala sekolah, dan anggota dewan. Kufoto lembar demi lembar, lalu bergegas keluar. Sebenarnya, ingin kucuri, tetapi takut ketahuan. Kuurungkan saja niat itu. Aku segera beranjak. Untunglah lantai dua sepi, hanya terdengar suara office boy menghidupkan keran air kamar mandi di dapur.
Aku bingung harus lewat pintu mana. Kucoba mencari jalan lain. Akhirnya, kutemukan sebuah pintu dan tangga yang tembus ke lantai satu. Tepat dekat gudang. Gudang itu menyimpan berkas yang tampak usang. Tenyata klien di kantor ini tidak hanya kepala daerah atau lembaga, tetapi juga para transgender yang hendak memalsukan identitas. Tampak dari foto-foto semula sebelum berubah. Ada yang bernama Bagas Purwanto, diubah menjadi Sagi Priwanti. Tohar Husnaidi menjadi Tina Hasnita. Meiwandi menjadi Meiliya Sari. Aku sempat geleng-geleng kepala.
Keblinger!
Di ruang resepsionis terdengar suara gaduh. Kedengarannya mereka sedang mencariku. Aku, si jurnalis yang lebih tepat dijuluki “Detektif Ulung” hampir berhasil mengelabui mereka. Aku mengendap-ngendap mencari pintu keluar. Namun, tida ada. Kucoba kembali ke atas (jalan semula) dan akan berpura-pura kesasar saat mencari toilet jika mereka curiga. Benar, aku hanya bisa lewat jalur semula. Di hadapanku telah berdiri lelaki bersafari cokelat tadi dengan wajah bengis, ”Hei, kau ini siapa? Ke mana saja dari tadi?”
“Saya kesasar mencari toilet, Pak.”
“Resepsionis, periksa dia!”
Resepsionis yang tadinya manis, tetapi seketika sinis itu memeriksa isi tas dan seluruh saku kemeja dan celana panjangku. Dia tidak menemukan apa-apa selain KTP milik temanku a.n. Ratna Kinanti, tempat/tanggal lahir: Depok, 11 Juni 1992, alamat: Tangerang, pekerjaan: wiraswasta, status: tidak kawin. Aku pun diminta untuk duduk sambil diintrogasi.
“Sebenarnya kamu ini mau apa, sih? Belum pernah ada klien selancang kamu?” cecar lelaki bersafari itu dengan emosi.
“Saya hanya ingin membuat ijazah palsu. Hari ini saya akan mengantar pas foto yang diminta kemarin.”
“Jika benar begitu, keluarkan pas fotomu! Kamu juga harus membayar uang senilai tiga juta karena harga ijazah palsu itu lima juta.”
“Tapi uang saya belum ada, saya hanya bisa melunasi jika ijazah sudah selesai, Pak.”
“Ah, tidak bisa. Lebih baik kamu pergi saja dan jangan pernah kembali! Kalau kere, jangan pernah ke sini!”
Aku langsung pergi tanpa berpamitan. Bagiku tidak masalah jika diusir begitu, asalkan apa yang kumau sudah kudapat. Mereka tidak hanya memalsukan identitas orang-orang, tetapi juga melakukan pemerasan.
Berdasarkan bukti-bukti otentik yang akurat, aku melaporkan perbuatan zalim mereka yang telah bersekongkol dengan para kepala daerah atau lembaga kepada polisi. Polisi mengapresiasi keberanianku mengungkapkan fakta. Mereka melakukan pengusutan lebih lanjut hingga berhasil membumihanguskan praktik dokumen ilegal ini beserta kepala daerah yang telanjur duduk manis menikmati jabatan empuk. Dalam hitungan bulan, beberapa kasus telah ditangani. Polisi berterima kasih, bahkan mengajak bekerja sama.
Aku semakin gencar membuat berita hot. Bukan untuk memprovokasi, melainkan mengungkapkan fakta tersembunyi. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat penghargaan dari media tempatku bekerja, gajiku pun naik, bukan hanya 10 persen, melainkan 20 persen. Aku pun bisa melanjutkan studi jurnalistik di kampus idaman. Sayangnya, sejak kejadian itu, aku sering mendapat teror dan banyak yang mengancamku. Aku tidak takut. Aku harus berani membuka tabir wajah-wajah pemalsu identitas yang penuh kehipokritan itu agar tidak banyak merugikan negara. Ya, akulah Niara Ikrari, seorang jurnalis yang tidak pernah takut kepada siapa pun, kecuali Tuhan.
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana dan Juara Harapan 3 Kompetisi Menulis Cerpen Majalah Komunikasi