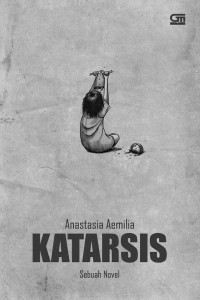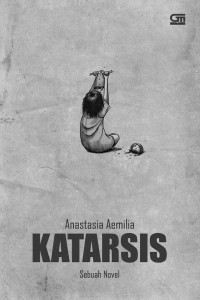Oleh Dwi Ratih Ramadhany
Judul : Katarsis
Penulis : Anastasia Aemilia
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Terbit : April 2013
Tebal : 264 halaman
Novel psychological thriller berjudul Katarsis ini terbilang mampu membuat pembaca terperanjat ngeri ketika terjerat ke dalam cerita yang memburu dan penuh misteri. Setelah kasus perampokan sadis yang merenggut nyawa terungkap, penulis lambat laun membuka tabir teka-teki peristiwa pembunuhan tragis itu. Tak perlu butuh waktu lama, pembaca bisa segera menangkap motif dari pembunuhan tersebut yang menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan perampokan yang melatarbelakangi tragedi tak terelakkan itu.
Tapi, setelah kasus pembunuhan itu dipaparkan, cerita tidak semena-mena berhenti melainkan terus menelurkan misteri tanpa terduga. Saat akhirnya Tara, tokoh utama dalam novel ini, menjadi target pembunuhan, pembaca seolah digiring masuk ke dalam kepingan cerita baru yang merupakan buah efek dari tindakan kriminal yang terjadi hampir dua puluh tahun silam dengan cara sadis tak kalah mengerikan.
Adegan demi adegan yang disuguhkan terasa menegangkan, terutama ketika penulis mendeskripsikan bagaimana si pembunuh membunuh korban-korbannya. Penulis dengan berani menuliskan bagaimana si pembunuh menyiksa korbannya, menutupi jejaknya, dan bermain dengan kotak perkakas seolah itu adalah kotak harta karunnya.
Namun, teror yang terjadi tidak cukup di situ. Tiba-tiba Jakarta dirundung resah dan takut. Kotak-kotak perkakas sejenis menjadi banyak ditemukan, berisikan manusia tanpa nyawa dan seperti tidak ada tanda perlawanan dari korban. Seolah, mereka masuk ke dalam kotak perkakas atas keinginan sendiri. Polisi pun dibuat ketar-ketir oleh keadaan ini.
Alfons, seorang psikolog yang merawat Tara setelah tragedi yang dipercaya sebagai perampokan, berusaha keras menyembuhkan Tara dari trauma. Paman Tara yang tiba-tiba menghilang setelah dinyatakan koma meyakini bahwa kasus pembunuhan berantai yang ada di sekitar mereka itu sebenarnya akan bermuara kembali kepada Tara, seolah ada dendam yang belum usai.
Kehadiran dua narator dalam menguak misteri tampak sesuai dengan metode katarsis. Kedua narator, secara gamblang, bercerita agar kita dapat memahami gejolak hidup mereka yang penuh tekanan. Novel ini menyuguhkan gagasan berbeda tentang anggapan traumatis sebagai alasan tindak kriminal seorang pelaku kejahatan. Bagaimana kalau tindakan kriminal itu dilakukan oleh manusia yang memang ditakdirkan untuk menjadi pelaku kejahatan sejak dilahirkan? Atau, bisa dikatakan mereka memiliki masalah psikologis. Bahkan, dalam novel ini, pelaku menganggap membunuh adalah sebuah media untuk mengobati rasa sakit hatinya atau menuangkan segala isi hati pelakunya.
Menggunakan dua narator –atau bahkan lebih- dalam novel memang tidak mudah. Terlebih ketika kedua narator ini memiliki sifat dan kecenderungan yang mirip. Sebut saja, Ello, orang yang Tara percaya karena merasa nyaman di sampingnya. Ternyata ia sendiri mengidap congenital insensivity yang membuatnya ingin selalu menyakiti dirinya sendiri tanpa merasakan sakit. Dan pembunuhan yang terus gencarkan olehnya, agaknya menjadi salah satu bentuk pelampiasan emosi yang tak mempan pada tubuhnya.
Kedua narator dalam novel ini menggunakan kata ganti ‘aku’ dan berkisah dengan cara yang identik. Ketika terjadi pergantian narator untuk pertama kali pada bab tiga, pembaca sedikit dibuat bingung. Namun, lambat laun ketika pembaca menyusuri bab-bab selanjutnya, pembaca akan menyadari kalau sudah terjadi pergantian narator dan tak lagi menyebabkan kebingungan meski pada bab-bab berikutnya sering terjadi pergantian narator.
Harus diakui bahwa novel debut Anastasia Aemilia ini memiliki premis yang menjanjikan. Ide yang brilian, dibumbui dengan teknik penulisan yang luar biasa, membuat kita bisa merasakan ketegangan di setiap babnya. Mengingatkan pembaca pada beberapa penulis horor dan thriller seperti Abdullah Harahap dan Edgar Allan Poe. Penggambaran karakter begitu hidup, deskripsinya sangat rinci, dan alurnya cukup rapi. Penggunaan sudut pandang orang pertama juga telah berhasil menyematkan nuansa ‘dingin’ pada karakter Tara.
Sayangnya, masih banyak lubang tak tertambal dalam novel ini. Tak ada penjelasan atau penggambaran yang masuk akal tentang mengapa Tara menjadi anak yang tak segan-segan memilih membunuh sebagai sistem pertahanan dirinya, seolah dia telah menjadi begitu haus darah sejak lahir dan membunuh menjadi hal yang wajar baginya.
Menuju bagian akhir, penulis terkesan terburu-buru dalam mengakhiri kisahnya. Tapi mengingat sejak awal kisahnya memang mengalir dengan cepat dan membuat napas pembaca seolah diburu, kemungkinan hal ini disengaja untuk menghasilkan efek serupa menonton film yang menegangkan. Bagian pamungkas sendiri akan membuat kita terkejut karena tidak terduga meski berakhir sederhana.
Kendati sebagai pembaca kita sudah tahu siapa pelaku pembunuhan di rumah keluarga Johandi, sebenarnya kasus yang dijadikan pembuka dalam novel ini tidak disajikan secara utuh. Hingga kita melewati halaman terakhir novel, polisi belum berhasil memecahkan kasus itu atau bahkan tak mampu menyusun kronologisnya.
Pada akhirnya, membaca katarsis menjadi sebuah rekomendasi untuk pembaca yang terjangkit rasa ingin tahu akut seperti apa sebenarnya yang terjadi dalam novel yang memikul kisah pelik ini. Bisa jadi Andalah yang menemukan siapa sebenarnya korban dan siapa pembunuh dalam kasus ini. Siapa tahu?
Peresensi adalah mahasiswa
Sastra Inggris. Resensi ini juara I kategori pustaka Kompetisi Penulisan Rubrik Majalah Komunikasi 2013.